Dibalik Musibah
05 December 2022
Tak sedikit orang yang berpikir bahwa musibah datang tersebab dosa yang kita lakukan. Artinya, musibah dipandang sebagai cara Allah “menghinakan” seseorang. Tak ayal, musibah yang menimpa saudara kita bukan mengundang empati, melainkan malah menyemburkan pikiran negatif. Lalu mencari-cari, “Apa kiranya dosa yang telah mereka perbuat, sehingga musibah itu bertubi-tubi memberondong mereka?”
Dengan dalih mendapatkan pelajaran dari musibah, namun sebenarnya ia sedang mencari aib orang lain. Padahal tidak ada kebahagiaan yang mengaliri hati selagi kita sibuk menelusuri aib orang lain. Bahkan tidak berhenti di pikiran, tapi berlanjut pada kata-kata yang menikam, menghujam, dan menyakiti.
Kita tak pernah tahu bagaimana rasanya ditimpa musibah, sehingga hendaknya kita tidak menambahi duka korban dengan “kutukan” dan penyudutan. Seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, di atas tangga ketambahan orang yang gemuk. Sakit di atas sakit. Bukan malah menolong, tapi justru mengutuknya.
Seharusnya ketika orang terkapar musibah, kita hadir untuk menghibur jiwanya, meneguhkan mentalnya, dan bahkan menyembuhkan deritanya. Bukan malah menambahi dengan rasa sakit yang lebih pedih. Jangan pernah kemudian menorehkan sebuah kesan bahwa musibah adalah sebentuk cara Allah menghinakan hamba-Nya.
Jika persepsi tersebut melintas di pikiran kita, maka kita menganggap orang yang tertimpa musibah sebagai sosok yang layak dihinakan. Ketika ada yang kita sudutkan dan rendahkan, tanpa disadari kita sedang meninggikan yang lain. Siapa yang kita tinggikan? Iya, kita sedang meninggikan diri kita sendiri. Berarti, masih terselip kesombongan di jiwa kita. Kita tahu, bahwa selagi orang digerogoti kesombongan, hatinya tak juga mencicipi kebahagiaan yang hakiki.
Jika persepsi ini dibangun dan dipupuk di tengah masyarakat, bahwa musibah merupakan pertanda kehinaan, sedangkan nikmat tanda kemuliaan, maka orang-orang yang berkelimpahan dan berkemakmuran secara ekonomi, kita anggap seorang mulia. Meskipun kita tahu, mereka sebenarnya abai bahkan tak pernah memenuhi hak-hak Allah sebagai sebagai Tuhan yang patut diibadahi. Sebaliknya, orang yang sering disergap musibah, kita anggap sebagai sosok yang hina meski sejatinya ia beribadah dengan tekun, sedekahnya rajin, wiridnya ajek, dan hubungan sosialnya apik. Allah sudah menyinggung kesalahan persepsi ini dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an.
Maka, adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku”. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku”. (QS. Al-Fajr [89] : 15-16)
Kesalahan persepsi ini kemudian berlanjut pada cara kita menyikapi kenyataan yang tidak kita inginkan. Ketika bertubi-tubi masalah memapar, lalu kemudian seseorang berkeluh kesah, “Ya Allah, bukankah saya sudah patuh pada-Mu, shalat sudah hamba jaga, sedekah sudah kutunaikan, kebaikan demi kebaikan telah kulakukan. Tapi mengapa Engkau masih saja mengujiku!”. Dia merasa sudah berbuat baik, tapi Allah masih saja mengujinya. Dia berpikir kalau orang-orang shaleh kehidupannya akan dibuat baik-baik saja, datar-datar saja, merangkum kesuksesan demi kesuksesan.
Anehnya, ketika dia terus mengeluhkan kenyataan yang membelitnya, pelan-pelan dia mulai tidak percaya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Dia berpikir, ibadah sama sekali tidak berdampak pada kebaikan nasib. Malah, terkesan, semakin ambruk. Jika sebelumnya, dia biasa melangkahkan kaki ke masjid, maka dia sudah mulai jarang, dan bahkan meninggalkan masjid. Kajian-kajian keagamaan sudah jarang didatangi. Bahkan dia melepas segala “simbol-simbol” yang menampilkan keberagamaannya.
Seorang wanita, pada mulanya dikenal sebagai orang yang sangat menjaga agama dalam kehidupannya. Dia menutup aurat, juga menjaga pergaulan dengan lingkaran orang shaleh. Sehingga tiba waktunya, dia menikah dengan seorang laki-laki pilihannya. Tidak berapa lama dia menenun hubungan rumah tangga, harus menerima kenyataan pernikahannya goncang, rapuh, dan berantakan. Dia dicerai oleh suaminya.
Setelah bercerai dengan suaminya, dia menjadi wanita tanpa lelaki sebagai tempat bersandar. Dia mencari pekerjaan dimana-mana. Dia mendapati pekerjaan, namun dalam lingkaran pergaualan yang sangat menjauhkan dari Allah. Dengan segala masalah yang sangat menyesakkan dadanya, dia mulai menjauh dari agama. Biasanya pakai jilbab, kini sudah dilepaskan dengan tanpa beban sama sekali. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil padanya. Dia berpikir, dia sudah banyak melakukan kesalehan, tapi Tuhan tak membalasnya dengan kebaikan.
Sudut pandang yang telah mengandung dua kesalahan. Pertama, dia merasa saleh, sehingga dia meminta dibalas dengan kebaikan juga. Merasa saleh—meski telah menjalani perbuatan saleh—tidak seharusnya menyeruak dari hati kita. Karena hal itu menandakan ada kesombongan yang terselip di jiwa. Kedua, dia telah salah persepsi tentang Allah dengan mengatakan, “Allah tidak adil”. Bagaimana Allah tidak adil. Allah tidak hanya adil, tapi juga ihsan.
Hanya saja penangkapan kita yang salah, sehingga kita justru tersakiti oleh kenyataan yang sama sekali di luar ekspektasi kita. Padahal, boleh jadi ujian tersebut sejatinya Allah hadirkan untuk meroketkan derajatnya di sisi Allah. Karena sikapnya yang salah, alih-alih musibah mendatangkan keberkahan, justru men-sirna-kan semua kebaikan sekaligus menenggelamkannya dalam penderitaan.
Jika orang lain terbelit musibah, mungkin sebagian menasihatinya untuk memperbaiki ibadah dan keimanan. Sekilas ucapan itu benar. Akan tetapi, tanpa disadari, kita telah memandang orang yang ditimpa musibah karena kurangnya ibadah dan kurangnya iman pada Allah. Selanjutnya, dipahamkan bahwa orang beriman itu tidak akan ditimpa musibah. Padahal, orang-orang beriman itu juga akan mendapatkan ujian. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka semakin besar badai ujian yang menghajarnya. Bukankah setiap ujian sebagai kesempatan untuk naik kelas?
Bagi orang yang imannya telah berbuah makrifat, setiap kenyataan sebagai bentuk kehadiran Allah Swt. Dikala memeroleh nikmat, maka respon yang diajukan adalah bersyukur, karena dibalik nikmat terselip rahmat dari Allah. Sebaliknya, ketika musibah yang datang menerpa, maka bersabarlah, karena disana kita menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa. Bukankah ketika kita tenggelam dalam kuasa Allah, iman kita tidak hanya berhenti sebagai kepercayaan, tapi juga sebagai piranti untuk bersandar atau berserah total pada Allah. Tatkala kita telah tiba pada stasiun penyerahan diri total pada Allah, kita akan selalu menyesap lezatnya spiritual.




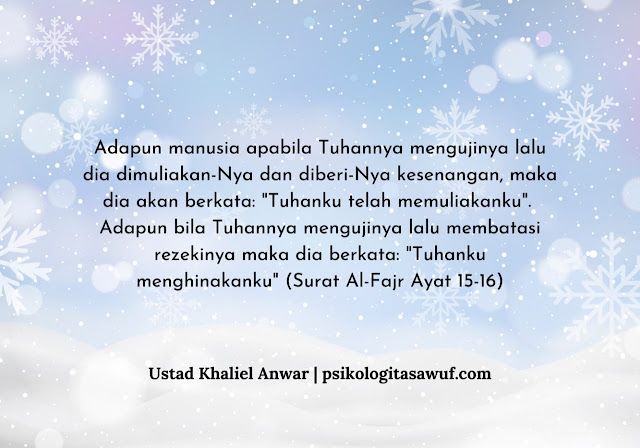
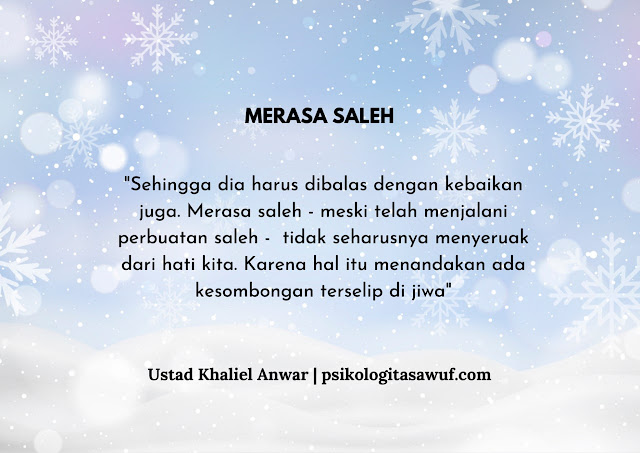

0 comments