Mengkhalifahi Kebahagiaan
08 December 2022
Sedari awal turun ke bumi, kita telah mendapati kesan bahwa Nabi Adam a.s.—meski “didepak” dari surga oleh karena menerabas larangan Allah—adalah orang besar. Orang besar bukan orang yang terbebas dari kesalahan. Boleh jadi, orang besar tergelincir dalam kesalahan, tapi dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Dia bukan sosok yang gampang melemparkan kesalahan pada orang lain. Begitulah potret karakter yang kita temukan pada Nabi Adam a.s. Beliau tidak menyalahkan Iblis yang jelas-jelas terus merongrong beliau agar tersingkir dari surga dengan berbagai godaan dan tipuan yang dilancarkannya.
Beliau juga tidak menyalahkan Ibunda Hawa, apalagi menyalahkan buah khuldi. Apalagi menyalahkan Allah. Sama sekali tidak. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Karenanya, beliau terus-menerus melangitkan doa pengampunan disertai tangisan penyesalan pada Allah. Dikisahkan, beliau bertobat pada Allah selama 200 tahun. Selama 200 tahun itu, beliau tak juga diterima tobatnya oleh Allah. Sehingga kemudian menyelipkan nama Muhammad Saw di antara doa-doanya.
Dari peristiwa tersebut, kita tak hanya menyaksikan jiwa kehambaan yang memancar pada Nabi Adam a.s, tapi juga menyaksikan ketidakjenuhannya untuk terus bertobat pada Allah Swt, karena merasa sebagai sosok yang lemah. Tentu, tanpa kasih sayang Allah, beliau akan terus berada dalam kesengsaraan dan kerugiaan sepanjang zaman. Selain itu, kita mendapati cermin sosok khalifah. Beliau bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Beliau tak melemparkan kesalahan pada siapapun. Dari situ, beliau sendiri yang memegang kendali penderitaan dan kebahagiaan dalam hidupnya.
Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzhalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi”. (QS. Al-A’raf [7] : 23)
Bahagia Bergantung Tafsir Dan Respon
Kebahagiaan bukan bergantung pada realitas yang tergelar, melainkan bergantung pada tafsir dan respon yang dibangun atas realitas yang tersaji tersebut. Selagi kita bisa memberikan tafsir positif, insya Allah perasaan positif akan mengaliri kita. Sebaliknya, jika yang menjalar penafsiran negatif, maka yang menumpuk di hati kita adalah perasaan negatif.
Ketika kita melihat ‘mawar yang berduri’, kita bisa memilih sebagai orang yang bahagia atau menderita. Jika kita fokus pada mawar yang tarus mekar, apalagi ada semerbak harum yang tercium, maka kebahagiaan kita juga terus mengembang. Akan tetapi, kalau perhatian kita tertuju pada duri yang menyeruak di antara mawar tersebut, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita.
Berbeda halnya, jika kita menafsirkan kembali bunga dan duri secara seimbang. Tentu kita akan menemukan kebahagiaan dari berbagai sisi. Melihat mawar, kita diluapi bahagia. Menatap duri, kebahagiaan kita juga tetap tak tercuri. Mengapa demikian? Karena kita berhasil “menarik makna” yang tersembunyi dibalik mawar dan duri. Menatap duri yang terbenak di pikiran kita, bahwa duri untuk melindungi mawar, agar tidak sembarang orang menyentuhnya. Hanya orang yang berani dan punya dignity yang bersedia memetiknya. Tanpa duri, setiap tangan sembarang meremas mawar. Mawar sendiri menyelipkan kebahagiaan, karena disana kita mereguk harum semerbak, ikut menyebarkan kesan positif ke dalam hati.
Banyak teman, mungkin, kita anggap baik. Sehingga kita merangkul serta beradaptasi dengan semua orang. Kita pun ingin selalu diterima semua orang. Padahal, kita yakin kita tak bisa memuaskan semua orang. Di sisi lain, salah seorang teman disingkirkan dalam circle-nya. Sudah tak lagi diterima dalam komunitas tanpa ada alasan yang eksplisit.
Mula-mula, disingkirkan dari komunitas dirasa sebagai musibah karena mengalami defisit jaringan. Kehilangan tempat berbagi. Tapi, kita tak pernah tahu apa tujuan Allah dibalik itu semua. Boleh jadi kenyataan tersebut untuk menghindarkan kita dari kehidupan yang rumit. Karena kalau kita hanya mengikuti arus, lantas terkesan tak punya prinsip dalam menjalani hidup, maka kebahagiaan kita hanya dikendalikan orang lain. Kehidupan kita digoyah-gayih oleh realitas di luar kita. Kita tak mengkhalifahi kebahagiaan kita sendiri.
Ketika disingkirkan dari manusia, tidak otomatis disebut orang yang hina. Bukankah manusia yang paling mulia pernah disingkirkan dan diusir oleh kaumnya? Tidak hanya diserang dengan kalimat yang merendahkan, bahkan secara fisik pernah mendapat perlakuan kasar. Akan tetapi, beliau tak pernah bersedih terlalu dalam oleh sebab kenyataan yang dialami. Beliau tak peduli dengan apapun yang mereka lakukan, asalkan Allah ridha pada beliau Saw.
Seorang guru berkisah perihal bagaimana beliau menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Setiap kali beliau mengendarai sepeda motor, beliau menyiapkan diri agar sepanjang perjalanan diiringi zikir pada Allah. Ketika jalanan macet, orang lain mungkin mengeluh, akan tetapi guru ini justru merasa nyaman, karena semakin lama waktunya untuk berzikir.
Akhirnya, kebahagiaan sangat terkait oleh sudut pandang dan penafsiran kita terhadap kenyataan. Tidak semua orang menyukai sakit. Akan tetapi, ketika sakit tiba, maka kita harus segera membangun sudut pandang untuk menyerap energi positif.
Boleh jadi sakit sebagai waktu kita untuk rehat, memuhasabah dan membenahi diri. Saking sibuknya kita, nyaris tak punya waktu untuk menelusuri, menjelajahi, dan membenahi diri sendiri. Lantas Allah memberinya sakit, untuk apa? Agar bisa menyapa diri sendiri lebih dekat. Menghitung nikmat demi nikmat Allah yang tercurah padanya.
Berpikir betapa banyaknya nikmat sehat yang sudah Allah berikan. Sakit mungkin hanya sebentar. Iya, kesulitan hanya sejenak. Tanpa sakit, maka sehat kurang terasa bermakna. Jika demikian, sakit meramu agar kesehatan yang telah dirasakan berlumur nikmat, dengan nikmat yang berlapis-lapis.
Kita tak bisa mengubah keadaan di luar, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Lalu cara pandang (point of view) membimbing kita bersikap. Jika kita memiliki sudut pandang yang baik, maka sikap yang terbit juga baik. Sebaliknya, jika kita punya sudut pandang negatif, maka berimbas pada sikap kita yang juga negatif. Ketika kita bersikap negatif, berikutnya yang turun ke dalam hati adalah “rasa negatif” berupa penderitaan.
Guru mulia Allah Yarham Syekh Dhiyauddin Kushwandhi dawuh, “Kita tidak bisa menggeser gunung, tapi kita bisa memotret gunung tersebut dari angle yang terbaik”. Begitulah, kita tak bisa mengubah kenyataan di luar, namun kita bisa mengubah sudut pandang kita tentang kenyataan. Disanalah akan kita temukan penafsiran terhadap kenyataan. Jika kita selalu menafsirkan secara positif, maka kebahagiaan akan selalu menemui kita.
Selama ini kita menggunakan sudut pandang hawa nafsu dan keakuan kita. Mengikuti selera kita. Jika kenyataan tak sejalan dengan selera, maka kita anggap buruk. Sebaliknya, kalau senafas dengan selera, lalu kita nilai baik. Nafsu selalu merasa kurang dengan setiap realitas yang terhidang di hadapannya. Iya, selalu terlihat kurang dalam kacamata hawa nafsu. Mungkin saja, kita menginginkan menu yang superlezat. Setelah menu itu sanggup terbeli, dan sudah terhidang di meja makan, tiba-tiba melintas di benak, jika ditambahi “ini dan itu” mungkin hidangan ini akan lebih enak.
Sementara keakuan, selalu ingin dikedepankan. Apa yang menjadi keinginan harus segera terpenuhi, harus diutamakan. Ingin selalu menjadi pusat perhatian dari orang lain. Karena dominasi hawa nafsu dan keakuan inilah manusia sering terbelenggu dalam ketidakbahagiaan.
Sekarang, apa yang harus kita tempuh agar penafsiran dan respon kita jernih dan selalu bisa membuahkan kebahagiaan? Penafsiran harus didasari iman yang sebenar-benarnya iman. Iman dengan makna cinta. Bukankah dalam kacamata cinta semuanya terasa indah? Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berprasangka baik dan sudah haqqul yaqin bahwa semua yang mengalir dari Allah hanya kebaikan.
Tidak ada keburukan sama sekali dari-Nya. Karena itu, situasi apapun yang menemui kita seharusnya tak pernah mengubah cara pandang kita tentang Allah. Dia adalah kebaikan mutlak. Jika kita tak temukan kebaikan, bukan karena tidak ada kebaikan, melainkan kebaikan itu masih disembunyikan, atau karena kebodohan kita sehingga tak bisa menyingkap kebaikan tersebut.
Secara lahir, terlihat kasar. Akan tetapi, energi yang mengalir di dalamnya adalah kelembutan. Seperti seorang kekasih yang mencubit kekasihnya. Sekilas kita berpikir bahwa cubitan itu sakit. Namun karena yang mencubit kekasihnya, maka dipandang sebagai bentuk hadiah yang paling berkesan dalam hidupnya. Allah kerapkali menimpakan ujian pada kekasih-Nya bukan sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai love-vibes.
Bukankah orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang yang derajatnya berada di bawahnya? Betapa indahnya ketika kita masih melihat orang yang diterpa ujian, namun senyumnya masih tetap mengembang lebar, wajahnya tetap berbinar-binar dan ucapan alhamdulillah terus mengalir dan menjalar. Tak pernah sedikit pun keluhan keluar dari bibirnya.
Jika demikian, pengendali dan pemilih kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Sementara orang yang sering menyalahkan orang lain dengan kenestapaan yang dialami, dia telah menyediakan diri sebagai objek yang dikendalikan oleh orang lain.
Ingatlah, yang paling bertanggung jawab terhadap kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak ditanya terkait perbuatan yang kita lakukan. Kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita sendiri. Dan orang yang dewasa akan bertanggung jawab dengan iklim kehidupannya sendiri. Karena seorang khalifah bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Dia bisa saja terpeleset dalam kesalahan, tapi dia berani mengambil resiko, mengakui kesalahan, dan berjuang untuk berbenah menjadi lebih baik.




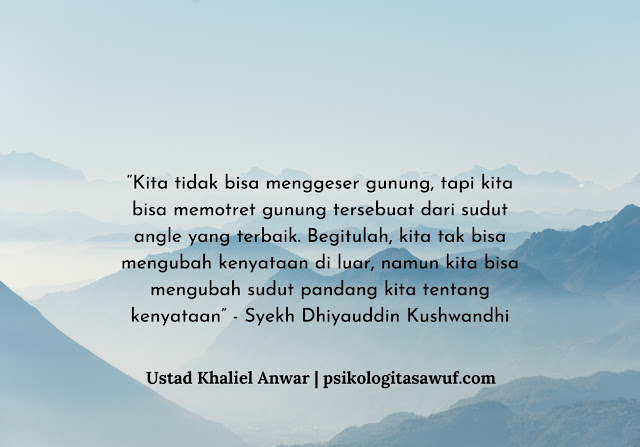


0 comments